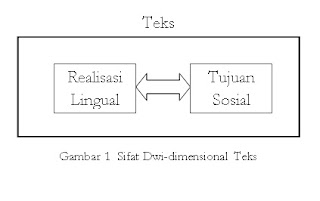5.1 Pengantar
Sebagai sebuah bentuk nyata bahasa dalam penggunaan, teks tidak hadir
dalam sebuah ruang sosial yang kosong. Kehadiran sebuah teks secara inheren
mengimplikasikan kehadiran unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain yang hadir
bersama teks tersebut disebut dengan konteks. Dengan kata lain, konteks adalah
yang menyertai hadirnya sebuah teks. Tidak ada pembicaraan mengenai konteks
tanpa ada teks. Begitu juga, tidak ada pembicaraan mengenai teks tanpa konteks.
Secara sepintas hubungan teks dengan konteks telah disinggung dalam Bab
4. Bahkan, konteks merupakan implikasi langsung dari definisi teks sebagai
realisasi lingual yang memiliki tujuan sosial. Dengan kata lain, tidak adak
teks yang tidak bersifat kontekstual karena teks merupakan bentuk nyata bahasa
dalam penggunaan dan, dengan demikina, berada dalam ruang sosial (social
sphere). Oleh karena itu, hubungan antara teks dengan konteks juga
merupakan dua sisi mata uang. Hal tersebut merupakan turunan langsung dari hubungan
antara realisasi lingual teks dengan tujuan sosial teks.
Pada kenyataannya, pengertian konteks secara umum menjadi tumpah tindih
sebagaimana pengertian teks. Tumpang tindih pengertian konteks tersebut
disebabkan oleh dan merupakan akibat langsung dari kekaburan pengertian istilah
teks yang diajukan oleh para linguis sebagaimana tampak dalam pembahasan Bab 3
dan bagian awal Bab 4. Tidak mengherankan apabila pengertian konteks sering
merujuk pada teks itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat pengertian yang
tumpang tindih antara teks dan konteks sehingga posisi dan peran keduanya
menjadi kabur. Kita akan membahas permasalahan tersebut pada akhir bagian ini
setelah pengertian konteks yang dipaparkan.
Bab 4 ini akan membahas permasalahan konteks dan secara lebih mendalam
relasi antara teks dengan konteks. Permasalahan konteks ini perlu dibicarakan
untuk mempertegas pengertian teks dan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud
dengan konteks dalam kaitannya dengan pengertian teks dalam Bab 4 bagian 4.4.
Di samping itu, pembahasan yang dilakukan juga akan mendalami hubungan antara
teks dengan konteks. Dengan memahami pengertian teks, konteks, dan hubungan
keduanya, kita dapat mengetahui dengan baik apa objek, metode, dan tujuan
analisis teks
5.2
Kajian Kritis tentang Konteks
Sumarlam (2003:47)
menyatakan bahwa “konteks wacana (teks)[1]
adalah aspek-aspek internal wacana (teks) dan segala sesuatu yang secara
eksternal melingkupi sebuah wacana (teks)”. Konteks internal teks tersebut
berupa bahasa dan konteks eksternal teks adalah konteks situasi dan budaya. Untuk
dapat melihat permasalahan yang ditimbulkan oleh definisi konteks tersebut,
definisi tersebut akan disajikan dalam bentuk gambar 5.
Menurut Sumarlam (2003)
Berdasarkan gambar 5,
tampak jelas bahwa konteks eksternal dan konteks internal memiliki kedudukan
yang sangat berbeda dalam hubungannya dengan teks. Konteks eksternal berdasarkan
gambar 5 tampak jelas berada di luar teks. Dapat juga dikatakan bahwa konteks
eksternal merupakan sesuatu yang berbeda dan dapat dibedakan dari teks. Sementara
itu, konteks internal berada dalam teks itu sendiri. Bahkan, dapat dikatakan
konteks internal tidak lain merupakan teks itu sendiri. Permasalahan yang
muncul adalah ketika hubungan antara teks dengan konteks internal dicemati
secara seksama.
Terdapat hubungan yang
tumpang tindih antara teks dengan konteks internal. Konteks internal adalah
aspek-aspek internal yang tidak lain adalah aspek-aspek realisasi lingual teks
itu sendiri. Konteks internal ini juga sering disebut dengan konteks
linguistik. Permasalahannya adalah jika
aspek-aspek internal teks yang berupa bahasa adalah konteks, maka teks itu
sesungguhnya adalah konteks karena teks tersusun atas aspek-aspek internalnya
yang berupa bahasa. Dengan demikian, apa bedanya antara konteks internal atau
konteks linguistik dengan teks itu sendiri? Bagaimanakah mungkin teks dapat
menjadi konteks bagi dirinya sendiri? Permasalahan tersebut muncul sebagai
konsekuensi logis dari ketidakjelasan definisi teks atau dalam definisi wacana
menurut para linguis yang telah dibahas dalam bab 3.
Untuk membahas secara
mendalam permasalahan hubungan antara konteks dengan teks, teks (IV.8) dalam
bab 4 disajikan kembali dalam (V.1).
(V.1)
a. Pembeli : Beli
b. Penjual :
Beli apa, Dik?
c. Pembeli :
Biskuat
d. Penjual :
Berapa, Dik?
e. Pembeli :
Dua
f. Penjual :
Ini
Menurut
definisi konteks yang diajukan oleh Sumarlam (2003:47), keenam kalimat dalam
teks (V.1) merupakan konteks internal. Akan tetapi, keenam kalimat tersebut
secara keseluruhan juga merupakan teks (atau wacana menurutnya). Yang menjadi
pertanyaan adalah ketika kita sedang melakukan analisis teks (V.1), kita
melakukan analisis teks atau analisis konteks. Di samping itu, manakah
batas-batas antara konteks internal dengan teksnya, sehingga kita dapat
mengidentifikasi manakah yang merupakan teks dan manakah yang merupakan
konteks?
Implikasi lebih jauh yang
diakibatkannya juga berkaitan dengan pembedaan yang selama ini dikenal dengan analisis
tekstual dan analisis kontekstual. Sumarlam (2006:22-31) menyatakan bahwa
“analisis tekstual adalah analisis wacana (teks) yang bertumpu secara internal
pada teks yang dikaji” dan “analisis kontekstual adalah analisis wacana (teks)
dengan bertumpu pada teks yang dikaji berdasarkan konteks eksternal yang
melingkupinya”. Kita ketahui bahwa baik analisis tekstual maupun analisis
kontekstual pada hakikatnya didasarkan pada konteks. Yang pertama didasarkan pada
konteks internal dan yang kedua pada konteks eksternal. Yang menjadi pertanyaan
mengapa hanya yang kedua yang disebut analisis kontekstual. Pembedaan analisis
tekstual dan kontekstual tersebut akhirnya mengisyaratkan bahwa analisis
tekstual bukanlah analisis kontekstual dan, dengan demikian, tidak berdasarkan
konteks.
Jika aspek-aspek internal
teks yang berupa bahasa merupakan konteks internal, maka analisis yang bertumpu
pada aspek-aspek internal teks secara logis juga harus dikatakan sebagai analisis
kontekstual. Tampak bahwa, sebagaimana pengertian teks, pengertian konteks juga
merupakan sesuatu yang selama ini dipandang sebagai hal yang sudah taken for granted, yakni hal yang
seolah-olah sudah kita pahami dengan jelas. Apa yang dapat kita lihat sejauh
ini adalah bahwa terdapat kekaburan apa yang disebut dengan konteks. Kekaburan
tersebut, sebagaimana selalu diingatkan dalam buku ini, disebabkan oleh
kekaburan pengertian teks dan wacana. Secara logis tentunya kita tidak dapat
menentukan konteks jika kita belum dapat menentukan teks.
Permasalahan konteks
dalam kaitannya dengan teks juga tidak dibahas secara jelas oleh Brown dan Yule
(1983), Lubis (1993), Schiffrin (1994), Eriyanto (2001), Sobur (2001), dan Rani
et. al. (2004). Mereka pada umumnya mencampurbaurkan (i) pengertian konteks
dari sebuah teks sebagai satu kesatuan seperti konteks dari teks maksimal (V.1)
dengan (ii) pengertian konteks dari teks-teks parsial pembentuk teks maksimal.
Kedua bentuk konteks tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam (i) konteks
linguistik dan konteks non-linguistik (Lubis 1993, Rani et. al. 2000), (ii)
konteks internal dan konteks eksternal (Sumarlam 2003), atau (iii) konteks
intrinsik dan konteks ekstinsik (Schegloff 1992). Kedua bentuk konteks yang
berbeda posisi tersebut, yaitu konteks dari teks maksimal dan konteks dari teks
parsial dan minimal, menurut mereka dianggap memiliki posisi yang sama, yaitu
sebagai konteks dari sebuah teks maksimal. Pengertian itu sama dengan
menyatakan bahwa, di samping konteks situasi dan budaya, konteks dari teks
maksimal (V.1) adalah teks-teks parsial dan teks-teks minimal dari teks (V.1)
itu sendiri.
Simpang siur pengertian
konteks tersebut tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan yang
ditimbulkan oleh definisi teks yang telah dibahas dalam bab 3. Saya sependapat
dengan Wood dan Kroger (2000:127) yang menyatakan konteks sebagai “information
that is outside the text being analyzed”. Akan tetapi, saya tidak
sependapat dengan Wood dan Kroger (2000:128) ketika mereka hanya menerapkan
konteks dalam pengertian ekstralinguistik seperti kelas, etnik, jender, suku,
kekuasaan, dan tatanan institusional seperti tatanan hukum. Pemahaman seperti
itu muncul karena definisi teks dipahami secara formal sehingga tidak melihat
kemungkinan teks sebagai realisasi lingual sebuah teks. Jika analisis
difokuskan hanya pada sebuah teks parsial yang terdapat dalam sebuah teks
maksimal, tentunya kita akan mendapati konteks lingustik di samping konteks
ekstralinguistik.
Pengertian konteks hanya
dalam pengertian konteks ekstralinguistik juga diajukan oleh Schiffrin
(1994:364) yang menyatakan bahwa konteks adalah
world filled
with people producing utterances: people who have social, cultural, and
personal identities, knowledge, belief, goals and wants, and who interact with
one another in various socially and culturally defined situations
Sebuah pengertian konteks yang diajukan oleh para linguis
selalu dapat dirujuk kembali pada pengertian teks yang mereka ajukan. Konteks
diartikan demikian karena teks menurut Schiffrin (1994:363) adalah “linguistic
material” sedangkan konteks adalah “envoronment in which “saying” ....
occur”. Tampaknya Schiffrin tidak menyadari bahwa “saying” atau teks
dapat terjadi dalam lingkungan teks lainnya seperti dalam sebuah percakapan
yang pada hakikatnya merupakan pertukaran teks antarpartisipannya. Meskipun
demikian, pengertian konteks menurut Schiffrin tersebut setidaknya
mengisyaratkna bahwa konteks berada di luar teks dan dapat digunakan ketika
kita berbicara tentang konteks ekstralinguistik.
5.3 Memamahi Pengertian
Konteks
Sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, konteks merupakan unsur-unsur di luar teks yang menyertai hadirnya
sebuah teks. Itu berarti bahwa secara tegas konteks berada di luar teks. Dapat
juga dikatakan bahwa batas antara teks dengan konteks dapat diidentifikasi
dengan jelas. Pengertian dasar konteks ini sama dengan apa yang dikatakan oleh
Wood dan Kroger (2000:127) bahwa konteks adalah “information that is outside
the text being analyzed”. Manakah yang menjadi konteks hanya dapat
diidentifikasi apabila manakah yang menjadi teks juga sudah dapat
diidentifikasi.
Berdasarkan definisi teks yang
telah disajikan pada Bab 4 bagian 4.4, hubungan antara teks dengan konteks
memiliki posisi yang jelas. Teks (V.1) adalah sebuah teks maksimal dengan tiga
teks parsial dan enam teks minimal. Keenam teks minimal penyusun teks (V.1)
membentuk sebuah teks maksimal sebagai satu kesatuan berdasarkan tujuan sosial
yang dimilikinya. Meskipun setiap teks minimal dan parsial memiliki tujuan
sosialnya masing-masing, semua teks minimal dan parsial tersebut dihasilkan
untuk mencapai tujuan sosial teks maksimal (V.1). Karena diikat oleh tujuan
sosialnya untuk melakukan transaksi barang dan jasa, keenam teks minimal dan
tiga teks parsial tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Oleh
karena itu, untuk memahami teks maksimal (V.1), kita harus memahami seluruh
teks mnimal dan teks parsial pembentuknya. Tentu saja, tujuan sosial transaksi
barang dan jasa tidak harus dicapai dengan melalui realisasi enam teks minimal
dan tiga teks parsial seperti teks (V.1). Tujuan sosial transaksi barang dan
jasa dapat dicapai dengan dua teks minimal dan dua teks parsial saja dan bahkan
sebuah teks maksimal dan sebuah teks parsial seperti tampak pada teks maksimal
(V.2) dan (V.3).
(V.2)
Pembeli :
Beli biskuat satu --- 1
(sambil memberikan uang)
Penjual : Ini -------------------- 2
(V.3)
Pembeli :
Beli biskuat satu --- 1
(sambil memberikan uang)
Penjual : (memberikan barang)
Dengan pengertian konteks
adalah yang menyertai teks dan yang berada di luar teks, kita dapat memahami
bahwa teks-teks minimal dan teks-teks parsial penyusun teks maksimal (V.1)
tersebut dapat saling menjadi konteks bagi satu dengan lainnya. Untuk dapat
memahami teks minimal (V.1.d), kita harus memperhitungkan teks minimal (V.1.a),
(V.1.b), (V.1.c), (V.1.e), dan (V.1.f). Dalam hal ini, teks minimal (V.1.a),
(V.1.b), (V.1.c), (V.1.e), dan (V.1.f) merupakan konteks bagi teks parsial (V.1.d).
Tanpa menyertakan teks (V.1.a), (V.1.b), (V.1.c), (V.1.e), dan (V.1.f) sebagai
konteksnya, kita tidak dapat memahami amanat teks minimal (V.1.d) ‘Berapa,
Dik?’. Akan tetapi, dengan menyertakan teks minimal (V.1.a), (V.1.b), (V.1.c),
(V.1.e), dan (V.1.f) sebagai konteksnya, kita dapat mengetahui bahwa amanat teks
minimal (V.1.d) ‘Berapa, Dik?’ adalah ‘Berapa banyak biskuat yang ingin
dibeli?’.
Meskipun amanat setiap
teks minimal yang terdapat dalam teks maksimal (V.1) dapat dipahami berdasarkan
teks-teks minimal lainnya sebagai konteksnya, apa yang dikandung seluruhnya
oleh teks maksimal (V.1) belum dapat dipahami jika belum dihubungkan dengan
konteks yang menyertai teks maksimal (V.1) sebagai satu kesatuan. Kita tidak
dapat mengatakan bahwa keenam teks minimal dan
tiga teks parsial pembentuk teks (V.1) merupakan konteks dari teks
maksimal (V.1). Dengan kata lain, keenam teks minimal dan tiga teks parsial
pembentuk teks maksimal (V.1) tidak dapat menjadi konteks dari teks maksimal
(IV.1) karena teks-teks minimal dan teks-teks parsial tersebut pada hakikatnya
adalah bagian dari teks maksimal (V.1) itu sendiri. Sementara itu, konteks
adalah unsur-unsur di luar teks. Jadi, konteks dari teks maksimal (V.1)
pastilah unsur-unsur selain teks-teks yang menjadi unsur pembentuknya. Relasi
antara teks parsial dengan konteksnya dan antara teks maksimal dengan
konteksnya dapat dilihat dalam gambar 6.
Gambar 6. Relasi antara Teks (V.1) dengan Konteksnya.
Dengan demikian, tampak
dengan jelas bahwa teks dan konteks memiliki posisi yang tidak tumpang tindih.
Konteks adalah unsur-unsur di luar yang menyertai teks. Oleh karena itu,
konteks dari teks maksimal (V.1) sebagai satu kesatuan adalah konteks situasi
dan budaya. Keenam teks minimal dalam teks maksimal (V.1) dapat menjadi konteks
hanya untuk teks minimal lainnya. Begitu juga, ketiga teks parsial dalam teks
maksimal (V.1) hanya dapat menjadi konteks untuk teks parsial lainnya. Keenam teks minimal dan ketiga teks parsial
tersebut tidak dapat menjadi konteks untuk teks maksimal (V.1). Karena
teks-teks minimal dan teks-teks tersebut merupakan bagian atau di dalam teks
maksimal (V.1) sebagai satu kesatuan, maka keenam teks minimal dan ketiga teks
maksimal tersebut tidak dalam posisi sebagai konteks dari teks maksmal (V.1). Memang benar bahwa untuk memahami teks
maksimal (V.1), kita harus memahami realisasi lingualnya yang berupa enam teks minimal
dan tiga teks parsial dan relasi teks – konteks di antara teks-teks minimal dan
parsial tersebut. Akan tetapi, sekali lagi enam teks minimal dan tiga teks
parsial terseut bukanlah dalam posisi sebagai konteks dari teks maksimal (IV.1)
sebagai satu kesatuan.
Dengan pengertian bahwa konteks
adalah semua informasi di luar teks yang sedang dianalisis, menjadi jelas bahwa
teks tidak dapat menjadi konteks karena keberadaan konteks berada di luar teks
yang berarti bukan teks itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian konteks yang
telah dijelaskan dalam bagian ini berbeda dari kecenderungan umum (mainstream)
yang menyatakan bahwa baik konteks internal maupun konteks ekternal merupakan
konteks dari teks maksimal. Pengertian konteks dan relasinya dengan teks yang
digunakan dalam buku ini dapat dikonfigurasikan dalam gambar 7.
Gambar 7. Konfigurasi Relasi antara Teks dengan Konteks
Hubungan yang digambarkan
dengan tanda panah (à)
dalam gambar 7 adalah hubungan kontekstual. Berdasarkan Gambar 7 tersebut,
tampak jelas bahwa teks dan konteks memiliki posisi yang berbeda dan
masing-masing dapat diidentifikasi sebagai objek yang berbeda. Dalam hal ini, konteks
selalu berada di luar objek yang disebut teks. Dengan kata lain, konteks selalu
bersifat eksternal. Deskripsi dalam Gambar 7 merupakan deskripsi abstrak yang
contoh nyatanya dapat dilihat pada gambar 6. Keduanya dapat dibaca secara
bersama. Teks maksimal (Tmaks) memiliki konteks sibu sebagai informasi yang
berada di luar teks maksimal yang sedang dianalisis. Teks maksimal (Tmaks) memiliki
realisasi lingual yang terdiri atas teks parsial (A) - (z) dan teks minimal (1)
– (n). Teks parsial (A) memiliki konteks (B, C, z) dan konteks sibu. Baik
konteks (B,C,z) dan konteks sibu berada di luar teks parsial A. Sementara itu,
teks minimal (1) memiliki konteks (2, n) dan konteks sibu. Begitu juga, konteks (2, n) dan konteks sibu
berada di luar teks minimal 1. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada bagian
dari teks yang menjadi konteks bagi dirinya sendiri sebagaimana disebutkan oleh
para linguis lain dengan istilah konteks internal atau konteks intrinsik.
5.4 Jenis Konteks
Ketika kita berbicara
tentang amanat sebuah teks, sering sekali kita meloncat menuju konteks. Kita
seolah melupakan bahwa konteks tidak memiliki arti sama sekali dan bahkan tidak
akan muncul tanpa adanya teks. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konteks ada
karena adanya teks. Begitu juga sebaliknya, teks ada karena adanya konteks.
Hubungan satu dengan lainnya adalah hubungan komplementer seperti dua sisi mata
uang. Meniadakan salah satunya berarti meniadakan yang lainnya. Oleh karena
itu, tidak pada tempatnya jika kita mengatakan salah satunya memiliki peran
yang lebih dari yang lain. Yang sesungguhnya perlu dicermati adalah bagaimana
teks berhubungan dengan konteks.
Berdasarkan pembahasan
bagian 4.1, kita mendapatkan dua jenis konteks. Dua jenis konteks tersebut
dibedakan berdasarkan tatarannya sesuai dengan yang dideskripsikan dalam gambar
6 dan gambar 7. Dua jenis konteks tersebut sama sekali tidak mempengaruhi definisi
konteks sebagai informasi di luar teks. Yang pertama adalah konteks dalam
pengertian konteks Sibu, sedangkan yang kedua adalah konteks dalam pengertian
Konteks (A-z) dan konteks (1-n). Konteks Sibu merupakan konteks untuk teks maksimal
dan juga berarti untuk teks parsial (A-z) dan teks minimal (1-n). Sementara
itu, Konteks (A-z) hanya menjadi konteks untuk teks parsial dan konteks (1-n)
hanya menjadi konteks untuk teks minimal.. Relasi antara konteks Sibu dengan
teks maksimalnya (Tmaks) membentuk koherensi kontekstual untuk teks maksimal (Tmaks),
yaitu keterpahaman teks secara kontekstual. Sementara itu, relasi antara
konteks (A–z) dan konteks (1-n) membentuk koherensi tekstual untuk teks
maksimal (Tmaks), yaitu keterpahaman teks berdasarkan realisasi ligualnya.
Penting diperhatikan
sekali lagi bahwa konteks (A–z) dan konteks (1-n) adalah konteks untuk teks
parsial dan teks minimal bukan konteks untuk teks maksimal (Tmaks). Itu
disebabkan karena teks parsial (A– z) dan
teks minimal (1-n) merupakan realisasi lingual teks maksimal (Tmaks) itu
sendiri. Dengan kata lain, teks parsial (A–z) dan teks minimal (1-n) adalah
wujud teks maksimal (Tmaks) itu sendiri. Oleh karena itu, tidak logis apabila
teks parsial (A–z) dan teks minimal (1-n) sebagai wujud teks maksimal (Tmaks)
menjadi konteks untuk teks maksimal (Tmaks) itu sendiri seperti dikonsepkan
dalam Analisis Variasi (Variation Analysis) bahwa “text itself became
a context” (Schiffrin 1994:375). Konsisten dengan pemahaman tentang relasi
antara teks dengan konteks yang tidak dapat dipisahkan, analisis teks, baik
dalam tataran koherensi kontekstual maupun tataran koherensi tekstual, selalu
bersifat kontekstual, yaitu didasarkan pada analisis terhadap teks dalam
kaitannya dengan konteks pada tatarannya masing-masing.
Dengan demikian, sejauh
ini kita dapat membedakan dua jenis konteks. Pertama adalah konteks yang
berkaitan dengan teks maksimal (Tmaks). Kedua adalah konteks yang berkaitan
dengan teks parsial (A-z) dan teks minimal (1-n). Kita tidak dapat
mencampur-baurkan kedua jenis teks tersebut karena memiliki posisi dan peran
yang berbeda. Konteks yang pertama adalah konteks situasi dan budaya, sedangkan
konteks yang kedua adalah konteks yang secara khusus untuk teks parsial dan
teks minimal. Konteks situasi dan budaya memiliki posisi di luar teks maksimal
dan, karenanya, secara otomatis juga berada di luar teks parsial dan teks
minimal. Konteks situasi dan budaya tersebut memiliki peran membentuk koherensi
kontekstual. Sementara itu, konteks yang kedua memiliki posisi yang berkaitan
dengan relasi antarteks parsial dan relasi antarteks minimal dalam sebuah teks
maksimal. Konteks tersebut memiliki peran membentuk koherensi tekstual. Konteks
yang pertama adalah konteks ekstralinguistik dan konteks kedua adalah konteks
linguistik. Akan tetapi, harus diingat bahwa konteks ekstralinguistik dan
konteks linguistik yang dimaksudkan di sini mempunyai pengertian yang sangat berbeda
dari dua jenis konteks yang telah diajukan oleh para analis wacana sebagaimana
disebutkan sebelumnya dalam bagian 5.2.
5.5 Rangkuman
Sebagai realisasi lingual
yang digunakan secara nyata dalam komunikasi, teks hadir dalam sebuah bingkai.
Bingkai yang mengemas hadirnya sebuah teks tersebut disebut dengan konteks.
Oleh karena itu, relasi antara teks dengan konteks merupakan relasi yang tidak
dapat dipisahkan. Teks sebagaimana telah didefinisikan dalam bab 4 secara
inheren mengimplikasikan bahwa tidak ada teks tanpa konteks. Akan tetapi,
sebagaimana permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam definisi teks,
berbagai pengertian konteks yang telah diajukan oleh para linguis juga memiliki
persoalan. Persoalan utama dari berbagai pengertian konteks yang telah ada
terletak pada (i) kekaburan identitas konteks dan (ii) kemungkinan konteks
mengacu pada teks itu sendiri. Dua persoalan tersebut mengakibatkan (i)
identitas konteks tidak dapat diidentifikasi dengan jelas dan (ii) konteks
dapat berupa teks itu sendiri.
Konteks di dalam bab 5
ini dengan tegas dipahami sebagai segala informasi di luar teks. Dengan kata
lain, letak konteks berada di luar teks. Itulah sebabnya konteks selalu
bersifat eksternal. Pengertian konteks tersebut memberikan identitas yang jelas
pada konteks. Identitasas konteks sebagai sesuatu yang berada di luar teks
merupakan patokan yang sangat jelas untuk melakukan identifikasi yang manakah
teks dan yang manakah konteks.Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan teks,
konteks dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak dimungkinkan mengacu pada
teks itu sendiri.
Secara umum terdapat dua
jenis konteks, yaitu (i) konteks linguistik dan (ii) konteks ekstralinguistik. Konteks
linguistik merupakan konteks yang berupa realisasi lingual, sedangkan konteks
ekstralinguistik merupakan konteks yang tidak berupa realisasi lingual. Konteks
linguistik hanya dimiliki oleh teks minimal dan teks parsial. Sementara itu,
konteks ekstralinguistik dimiliki oleh teks minimal, teks parsial, dan teks
maksimal.
[1]
Penulisan “…wacana (teks) …” berarti bahwa kata wacana merupakan bentuk asli yang
dikutip dari sumbernya dan kata (teks) adalah tambahan penulis yang dalam buku ini
termasuk dalam definisi teks. Karena wacana dan teks dalam buku sumber tidak
dibedakan, penyebutan teks dalam dua kurung (teks) dalam buku ini memberikan
pemenakanan adanya pembedaan di antara keduanya.